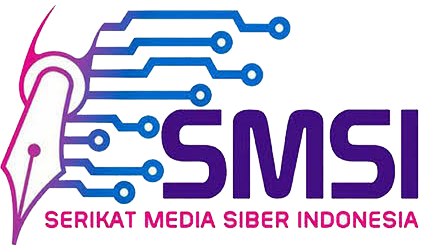Oleh Syafruddin AL
PADA masa lalu, nama-nama besar seperti Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Haji Agus Salim tidak sekadar dikenang karena kebesaran nama, tetapi karena keluasan pandang dan keberanian berpikir melampaui sekat-sekat kedaerahan. Para intelektual Minangkabau ini menjadikan ide sebagai kendaraan untuk menembus ruang-ruang nasional, bahkan membentuknya. Mereka tidak menunggu ruang untuk berbicara—mereka menciptakannya. Mereka tidak sekadar hadir dalam sejarah—mereka mengukirnya.
Yang menarik, meski berpikir dalam kerangka nasional, mereka tidak mengabaikan kampung halaman. Tanah Minang tetap hadir dalam nalar mereka—tidak dibicarakan secara partikular, tetapi diinklusikan dalam visi nasional mereka. Jika ada hal yang dianggap tak sejalan, mereka mengingatkan—bukan untuk mencela, tapi untuk menjaga. Mereka tidak mencikaraui kampungnya sendiri. Justru, mereka menjaganya dengan cara yang lebih besar: lewat keberhasilan mereka memperjuangkan kepentingan bersama.
Namun, pasca peristiwa PRRI dan ketegangan relasi pusat-daerah yang menyertainya, tampak ada sumbatan kolektif dalam aliran pikiran dan gerakan urang awak ke tingkat nasional. Sebuah dekadensi mental yang pelan tapi konsisten: dari semangat menciptakan ruang, menjadi sekadar mencari ruang; dari kepemimpinan wacana nasional, menjadi pengikut narasi yang sudah tersedia. Melesatnya seseorang kini lebih karena manuver personal, bukan dorongan kolektif yang sadar dan terstruktur.
Ironisnya, dalam beberapa dekade terakhir, semangat perantau justru semakin tersedot pada hal-hal teknis yang seyogianya menjadi domain pemerintah daerah dan tokoh lokal. Ada kecenderungan elit rantau untuk terlalu ikut campur dalam urusan-urusan operasional kampung, bahkan ketika kapasitas mereka semestinya diarahkan untuk mendorong kemajuan melalui peran strategis. Bukannya memfasilitasi ide dan memberikan inspirasi dari luar, mereka sering kali malah menjadi pelaku langsung di medan lokal, kadang tanpa melibatkan masyarakat kampung sejak awal.
Inilah yang disebut dengan “membawa ide dalam kambut”—sebuah kiasan bahwa program-program yang dibawa dari rantau sering kali datang dengan isi dan logika yang sudah tertutup, tanpa transparansi, tanpa kolaborasi. Masyarakat di kampung pun hanya menjadi obyek, bukan subyek dari pembangunan. Padahal, esensi kekuatan Minangkabau selama ini justru terletak pada dialog—pada duduk bersama, pada musyawarah mufakat yang bukan hanya simbol, tapi tradisi kognitif.
Maka, seharusnya peran perantau dan elit rantau tidak terjebak pada hal-hal teknis yang bisa ditangani oleh struktur lokal. Sebaliknya, mereka harus tampil sebagai aktor perubahan di tingkat nasional—menginspirasi, membentuk opini, dan menegaskan kembali identitas intelektual Minang sebagai penggerak bangsa, bukan sekadar pelengkap di meja kekuasaan.
Kita merindukan suara itu. Suara yang tidak hanya nyaring, tapi bernas. Suara dari tanah Minang yang mengguncang nasional bukan dengan retorika kosong, tapi dengan ide-ide besar. Kita rindu tokoh yang bukan hanya bicara tentang Minang di Minangkabau, tetapi tentang Indonesia dari sudut pandang Minangkabau. Kita rindu menjadi penyetir narasi, bukan hanya penumpang atau pengikut dari peta yang digariskan pihak lain.**
*Penulis adalah wartawan senior yang kini bermukim di Jakarta.