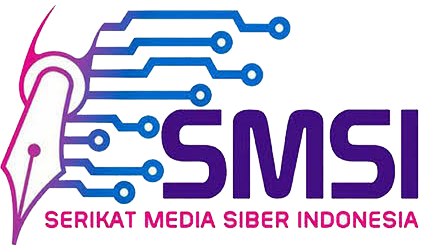Oleh : Denni Hidayat
(Kolumnis Lepas)
Latar Belakang
DALAM interaksi sosial, kita sering berasumsi bahwa kebaikan adalah bahasa universal yang akan dipahami oleh setiap manusia. Namun, realitas menunjukkan adanya paradoks: semakin baik seseorang memperlakukan orang lain, terkadang justru semakin besar tekanan dan ketidakadilan yang ia terima.
Fenomena ini bermuara pada perbedaan mendasar dalam tingkat kesadaran. Ada individu yang bergerak dengan kesadaran moral yang tinggi, ada pula yang masih terjebak dalam tingkat kesadaran moral yang rendah, di mana naluri hewani lebih dominan daripada nilai-nilai kemanusiaan.
Ketidaksamaan frekuensi inilah yang menyebabkan niat baik sering kali tidak berakhir pada kedamaian, melainkan pada eksploitasi inilah yang dimaksud sebagai kerumitan hati manusia, terutama bagi manusia yang berkesadaran rendah dengan kesadaran hewani yang tidak bisa memandang suatu kebaikan dengan rasa terima kasih dan penghargaan.
Semakin rendah tingkat kesadaran seseorang maka dia menganggap bahwa kehidupan ini adalah permainan zero sum game tidak ada konsep win-win solution atau toleransi, sebagai contoh semakin baik kita kepada seseorang, semakin mereka mengira kita rela dirugikan dan mereka merasa telah memenangkan permainan, ketika kita tidak membalas mereka mengira kita sudah takut, karena itu mereka akan terus menguji batas kesabaran dan melanggar garis kita berulang kali dengan memperbesar hak mereka sendiri dan perlahan menekan ruang hidup kita, ini bukan karena mereka jahat melainkan karena memang mereka tidak memiliki konsep hidup berdampingan dan sinergi, yang ada hanya menang atau kalah ditindas atau menindas dan lucunya kita masih mengharapkan pengertian dan rasa terima kasih dari mereka.
Pokok Permasalahan
Masalah timbul ketika individu berkesadaran tinggi mencoba membangun hubungan menggunakan instrumen empati terhadap mereka yang memiliki kesadaran diri rendah. Bagi individu dengan kesadaran rendah, empati dan sikap mengalah tidak diterjemahkan sebagai bentuk penghormatan, melainkan sebagai sinyal kelemahan.
Mereka tidak memiliki kapasitas kognitif untuk memahami niat baik (altruisme). Akibatnya, hubungan tidak lagi menjadi ruang untuk hidup berdampingan, melainkan menjadi medan perang di mana pihak yang lembut dianggap sebagai mangsa dan pihak yang keras dianggap sebagai pemenang.
Di sini, logika bertabrakan dengan naluri predator hewani, dan niat baik berbenturan dengan hasrat primitif untuk mendominasi. Orang yang memiliki kesadaran rendah tidak bisa didekati dengan model kebaikan yang manusiawi, sebagai contoh mungkin tidak semua orang layak menerima kebaikan anda, terkadang setiap niat baik yang anda berikan akan berubah menjadi tuntutan demi tuntutan menuju titik yang tidak memiliki batas, sementara anda mengira sedang membangun hubungan baik dengan mereka, sedang disisi lain mereka menganggap anda adalah budak yang harus menghamba kepada mereka, rumit dan serba salah bukan ? sekarang mari kita lihat fakta penelitiannya.
Hasil Penelitian
Landasan teoretis pertama berakar pada model Triune Brain yang dikembangkan oleh neurosaintis Paul D. MacLean. Dalam perspektif psikologi evolusioner, Dia mengatakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari lapisan-lapisan yang mencerminkan tahapan evolusi, di mana "otak reptil" (batang otak) dan sistem limbik bertanggung jawab atas fungsi kelangsungan hidup, insting agresif, serta emosi dasar seperti rasa takut dan dominasi.
Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang berada pada tingkat kesadaran diri yang rendah, aktivitas saraf mereka lebih dominan di area ini, yang menyebabkan mereka merespons stimulus sosial secara reaktif dan impulsif. Hal ini menjelaskan mengapa niat baik sering kali ditanggapi dengan naluri predator, otak mereka secara otomatis memetakan lingkungan sosial sebagai medan kompetisi bertahan hidup, bukan sebagai ruang kolaborasi kognitif yang dikelola oleh prefrontal cortex.
Teori ini didukung oleh Daniel Goleman dalam kaitannya dengan persepsi interpersonal, psikolog ini mengajukan konsep Kecerdasan Emosional (EQ) menekankan bahwa kemampuan untuk berempati dan memahami niat orang lain memerlukan kematangan fungsi kognitif yang tinggi. Individu dengan kesadaran diri rendah mengalami apa yang disebut sebagai keterbatasan dalam Theory of Mind, yaitu ketidakmampuan untuk memahami bahwa orang lain memiliki perasaan, niat, dan motivasi yang berbeda dari diri mereka sendiri.
Akibatnya, mereka gagal menginterpretasikan perilaku altruistik atau sikap mengalah sebagai bentuk moralitas tinggi. Sebaliknya, mereka terjebak dalam bias kognitif yang menyederhanakan interaksi menjadi sinyal kekuatan fisik atau dominasi, jika Anda memberi, maka dalam skema kognitif mereka itu bukan karena anda peduli atau berempati, melainkan karena anda berada dalam posisi subordinat atau lemah.
Kemudian fenomena ini didekati dengan pendekatan psikologi sosial dengan memperdalam melalui Teori Zero-Sum game, sebuah konsep yang sering diteliti dalam konteks perilaku kompetitif oleh para ahli seperti John von Neumann dan dikembangkan lebih lanjut dalam psikologi oleh Robert Axelrod. Dalam kerangka berpikir individu berkesadaran rendah, dunia dipandang sebagai tempat di mana sumber daya termasuk perhatian, rasa hormat, dan keuntungan bersifat terbatas dan tidak dapat dibagi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang dengan karakteristik ini memiliki scarcity mindset (pola pikir kelangkaan) yang ekstrem, sehingga mereka merasa bahwa untuk menjadi "pemenang", mereka harus membuat orang lain menjadi "pecundang". Mereka tidak memiliki kapasitas untuk memahami hubungan Non-Zero-Sum atau sinergi, di mana kedua belah pihak bisa tumbuh bersama melalui rasa saling menghargai dan mau juga untuk saling berbagi.
Selanjutnya B.F. Skinner dengan konsep operant conditioning psikologis menjabarkan, ketika seseorang terus memberikan kebaikan kepada individu yang beroperasi dengan naluri primitif tanpa memberikan batasan yang tegas, maka orang tersebut secara tidak sengaja "menghargai" perilaku manipulatif mereka.
Karena mereka melihat kebaikan adalah sebagai hasil dari dominasi, mereka akan mengulangi perilaku tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penelitian dalam psikologi klinis menunjukkan bahwa tanpa adanya feedback berupa konsekuensi atau ketegasan, individu dengan kesadaran rendah tidak akan pernah mencapai titik pemahaman moral yang baik.
Oleh karena itu, ketegasan bukanlah bentuk kekejaman, melainkan kebutuhan psikologis untuk menyeimbangkan hubungan agar tidak terperosok ke dalam eksploitasi hubungan yang merusak kesehatan mental baik bagi yang memberi maupun yang menerima dan ini hanya bisa dicegah dengan memberikan kebaikan yang berintegritas.
Kebaikan yang beritegritas
Jalan keluar dari bentuk hubungan eksploitatif ini bukanlah dengan berhenti menjadi orang baik, melainkan dengan memahami bahwa kebaikan harus memiliki aturan dan batasan. Kita tidak bisa menggunakan model pendekatan "peradaban manusia" untuk menghadapi individu yang masih menggunakan "naluri hewan" egoisme diri mereka.
Kebaikan harus dipandang sebagai sebuah kekuatan, bukan kewajiban moral yang dipaksakan kepada orang lain. Individu berkesadaran tinggi harus mampu membaca dinamika kerumitan hati orang berkesadaran rendah dan menyadari bahwa tidak semua orang layak menerima kelembutan dalam bentuk kebaikan hati.
Penegakan batasan kebaikan yang berintegritas mungkin adalah satu bentuk bahasa yang dapat dipahami oleh mereka yang hanya mengenal konsep kuat-lemah, untung-rugi dan menang kalah dalam melakukan interaksi sosial. Kebaikan yang Berintegritas adalah suatu konsep di mana tindakan baik seseorang tidak lagi muncul dari kepatuhan buta, rasa takut akan konflik, rasa takut kehilangan, atau kenaifan diri, melainkan dari pilihan sadar yang berlandaskan pada nilai kedaulatan diri yang menghasilkan keberlanjutan kebaikan dengan batas-batas yang tegas.
Penutup
Sebagai kesimpulan, penting untuk dipahami bahwa kebaikan tanpa kekuatan adalah ketidakberdayaan, sedangkan kekuatan tanpa kebaikan adalah tirani. Hidup berdampingan yang saling menghormati menuntut setiap orang untuk memiliki "Kebaikan beintegritas ". Manusia harus memperlakukan manusia lainnya sebagai sahabat, bukan sebagai alat, namun juga harus memiliki keberanian untuk menghentikan siapa pun yang mencoba menjadikan diri kita sebagai alat mereka.
Ketika setiap orang menyadari bahwa ruang hidup mereka berakhir di tempat ruang hidup orang lain dan saling bergantungan, maka dari situ akan timbul rasa hormat antar manusia, dan kondisi inilah yang seharusnya diciptakan, itu baru layak disebut sebuah peradaban.**